
Ketika Tou Minahasa Harus Melawan
(Sepenggal Cerita Tentang Permesta dalam Ingatan Para Pelakunya)
Oleh: Denni Pinontoan (Penulis, Akademisi, Pegiat Mawale Movement)
“Merdeka!!” teriak sekelompok orang, ketika Soekarno, presiden Indonesia itu datang ke Gereja Sion Tomohon di tahun 1957. Massa yang menjemput Soekarno serempak dan spontan balas menjawab dengan teriakan yang lebih keras: ”Permesta!!!” Begitu yang terekam dalam ingatan Jus Pangemanan, seorang eks anggota Kompi Mahasiswa Permesta (Perjuangan Semesta).
”Lalu bagaimana reaksi Soekarno waktu itu, opa?” tanyaku.
”No, dia mo bilang apa? Waktu itu hele rumpu Permesta no!” jawab Jus.
Waktu Soekarno datang di Tomohon tahun 1957 itu, Jus kelas akhir SMA Negeri di Tomohon. Kata Jus, waktu itu, sepanjang jalan Tomohon ramai dengan warga dan anak sekolah yang menyambut presiden pertama Indonesia itu. ”Waktu Soekarno datang itu, dia nae Jeep. Tu jalang basar yang dia mo lewat akang, banyak siswa deng warga yang da ba rei,” kata Jus yang ternyata masih ingat betul peristiwa yang terjadi 52 tahun silam itu.
Setahun kemudian, Jus mendaftar di Akademi Angkatan Laut Surabaya. ”Tiga bulan kita kita so iko pendidikan di sana. Tapi, karena pusat nda mau ada orang-orang Permesta, maka kami dipulangkan ke Minahasa,” ujar Jus mengenang.
Di Minahasa Jus kemudian mendaftar di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (cikal bakal IKIP) di Tondano. Tapi, kata Jus, waktu dia baru mulai kuliah, di tahun 1958 itu, tentara Pusat datang membom RRI di Manado dan Gunung Maria di Tomohon. Maka, pecahlah perang! Jus pun jadi tentara Permesta Kompi Mahasiswa.
Jus, kini tinggal di Kotabunan – salah satu daerah pesisir di Boltim – daerah pemekaran baru itu dengan puas menerima uang pensiunan sebagai mantan pegawai negeri. Rasa puasnya itu, seolah-olah dibuktikan dengan kemeja batik Korpri yang ia kenakan di saat kami (saya, Greenhil Weol, Rikson Karundeng dan Andre Barahami) mewawancarainya pada Agustus 2008 di Kotabunan.
Umur Jus sekarang memang sudah sudah uzur, berkisar di 70-an tahun. Tapi, kalau menyinggung Minahasa dan Permesta, bicaranya masih penuh semangat. Tampak sekali kebanggannya menjadi orang Minahasa yang penah terlibat dalam gerakan menentang pusat yang waktu itu dianggap telah melakukan ketidakadilan terhadap tanah ini. Keriput di wajahnya, seolah kontras dengan semangat Permestanya itu. Dan, sebagai seorang Katolik kadang bicara Jus tentang Minahasa bercampur dengan keyakinan agamanya.
David E. F. Henley mengutip Barbara Harvey, antara lain mencatat latar belakang gerakan Permesta itu dengan menyebut adanya persoalan monopoli pembelian kopra oleh pemerintah pusat. Ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara Minahasa dan Pusat. Henley menyebut gerakan Permesta sebagai puncak keluhan warga Minahasa atas ketidakadilan tersebut.
Julius Semet, seorang eks Corps Tentara Pelajar (CTP) Permesta, yang kini memikmati usia tuanya dengan tenang di wanua Tincep kecamatan Sonder, antara lain mengatakan, menjadi tentara Permesta waktu itu, adalah juga karena bahwa dia orang muda Minahasa yang harus menunjukkan kepada pusat bahwa orang Minahasa tahu berperang. Tapi, menurut laki-laki mantan guru SD dan Majelis Jemaat GMIM Tincep ini, persoalan yang memicunya adalah karena ketidakadilan di bidang ekonomi. (wawancara dengan Julius Semet ini dilakukan oleh Mawale Movement pada 19 April 2009, di Wanua Tincep).
Waktu Permesta pecah Guru Utu bersekolah di Sekolah Guru Bawah (SGB), di Kuranga Tomohon. Dia bersekolah di situ dari tahun 1954 hingga tahun 1958.
“Pamer keberanian melawan ketidakadilan, arahnya membangun. Kedua, anti komunis,” kata laki-laki yang dikenal orang-orang se-Sonder dengan panggilan Guru Utu itu menjelaskan alasan dia ikut dalam gerakan Permesta.
Guru Utu masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Letkol Saleh Lahade, salah seorang Dwitunggal petinggi Permesta asal Makasar itu ketika datang ke Minahasa untuk memprogandakan perjuangan Permesta.
“Kita punya hasil kopra satu drum dikirim ke Jakarta, dikembalikan cuma satu blek susu. Adil atau tidak?!” kata Lahade.
“Tidak!!” jawab Guru Utu dan teman-temannya.
“Siap angkat senjata!?”
“Siap!!”
“Jalan di sana (barangkali maksudnya pulau Jawa/Jakarta – saya), jalan-jalan aspal. Jalan-jalan kita jalan gonofu samua!!! Ayo angkat senjata!!”
“Siap!!”
“Berani?!”
“Berani!”
Begitu kata Guru Utu merekam dialog mereka dengan Lahade waktu itu.
Padahal, menurut Guru Utu, amunisi untuk berperang sebenarnya tidak memadai. Selain itu, ketrampilan berperang juga mereka tidak punya. Sehingga, menurut Guru Utu, waktu itu ada beberapa temannya yang menjadi korban senjata sendiri karena tidak tahu menggunakan senjata. “Tapi mengapa kami berani berperang?” ujarnya.
“Yang menjadi daya tahan kami,” lanjut Guru Utu, “adalah semangat Minahasa. Waktu itu, darah muda, penuh semangat dan keberanian. Sedangkan tua-tua berani, apa lei torang masih muda waktu itu.”
Tapi, di balik kebanggaan itu, Guru Utu menyesali juga terjadinya baku curiga atau bahkan baku tembak antara anak Minahasa sendiri. “Tapi sayangnya, karena perang itu, saudara bersaudara saling perang,” ungkapnya menyesali perang itu.
Guru Utu, sebenarnya datang ke Minahasa nanti pada tahun awal 1950-an. Masa anak-anak dan remajanya dihabiskan di Magelang, tempat kelahirannya. Ayahnya seorang tentara NICA asal Minahasa, sementara ibunya masih keturunan keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, sempat ditawan di Ambon oleh Jepang di masa-masa perjuangan kemerdekaan. Nanti bertemu dengan ayahnya, tahun 1947. “Semasa kecil, kakek, ayah dari ibu yang mendidik saya. Kakek saya itu seorang Jawa dan Islam yang taat,” kata Guru Utu.
Waktu datang ke Minahasa Guru Utu tinggal di wanua Tincep, sebuah daerah yang dicatat oleh Graafland sebagai negeri yang terkenal dengan air terjunnya. Di wanua ini, dia mengenal banyak tentang kebiasaan dan pandangan hidup orang Minahasa. Tapi, juga, sebelumnya, kakek dari pihak ayahnya telah memperkenalkan dia banyak hal tentang Minahasa.
Cerita tentang Permesta, yang masih terekam jelas dalam ingatan Jus dan Guru Utu ini, dua orang dari begitu banyak pelaku pelaku Permesta di Minahasa (band. dengan ungkapan banyak orang Minahasa hingg kini: “Sampe rumpu lei Permesta”) seolah-olah ingin membenarkan perkataan Samratulangi di Nederland pada 28 Maret 1914: “Saya tidak akan mempermasalahkan apakah keberadaan bangsa kami disukai atau tidak, karena itu adalah permasalahan teoritis. Bagi saya dan bangsa saya Minahasa, sudah jelas, bahwa kami memiliki hak untuk eksis.” Samratulangi menyampaikan itu dalam tulisannya yang berjudul “Het Minahassisch Ideaal” yang kemungkinan disampaikan dalam sebuah ceramah. (***)





.jpeg)
































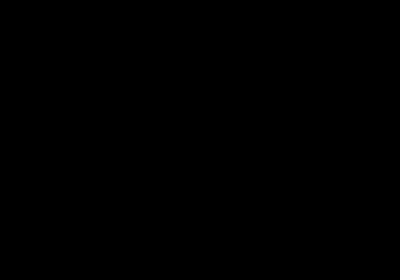
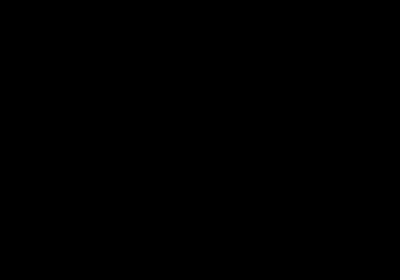
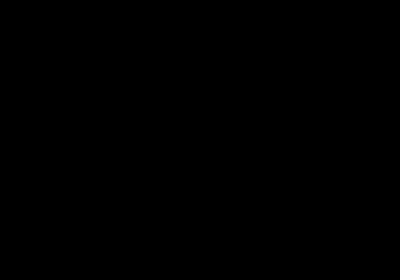










Komentar